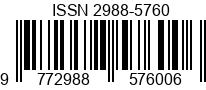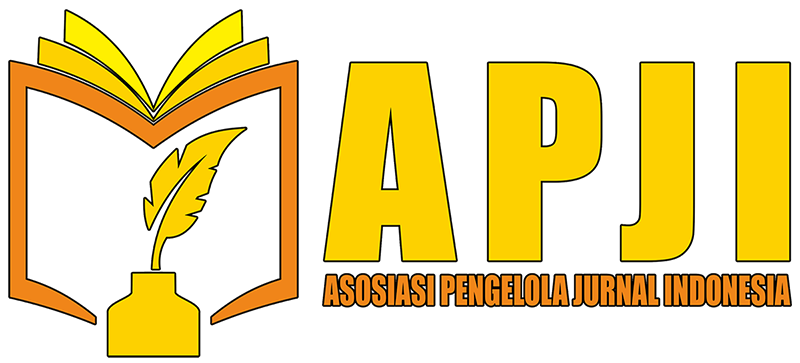Implementasi Nilai Pawongan Dalam Kegiatan Membuat Canang Untuk Membentuk Karakter Gotong Royong Peserta Didik Kelas VII 8 SMP Satu Atap Negeri 2 Ampibabo
Main Article Content
Ni Wayan Suparni
Gotong royong, sebagai salah satu nilai luhur budaya Indonesia, memiliki peran penting dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan saling mendukung. Nilai ini tidak hanya relevan dalam kehidupan sosial, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam dunia pendidikan. "Gotong royong merupakan wujud nyata dari kebersamaan dan kesatuan masyarakat Indonesia dalam menghadapi tantangan bersama," sebagaimana diungkapkan oleh Geertz (1961) dalam penelitiannya mengenai masyarakat Jawa. Dalam konteks pendidikan, gotong royong dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan kolaboratif, di mana setiap peserta didik saling membantu untuk mencapai tujuan bersama.
Namun, dalam kenyataannya, tidak semua peserta didik memahami dan menerapkan nilai gotong royong dalam proses belajar. Fenomena siswa yang egois, tidak mau membantu teman sekelas, dan selalu ingin menang sendiri semakin sering ditemukan. Menurut penelitian oleh Rachmadi (2019), "sikap egois di kalangan pelajar sering kali disebabkan oleh tekanan untuk berprestasi secara individual, sehingga mengesampingkan pentingnya kerja sama dan saling mendukung." Sikap ini tidak hanya merugikan teman sekelas, tetapi juga merugikan diri sendiri karena mereka kehilangan kesempatan untuk belajar dari orang lain dan mengembangkan keterampilan sosial yang penting.
Sikap egois ini juga berdampak negatif pada dinamika kelas, di mana suasana belajar menjadi kurang kondusif dan penuh dengan persaingan yang tidak sehat. Dalam studi oleh Suryadi (2020), ditemukan bahwa "kelas dengan tingkat individualisme yang tinggi cenderung memiliki tingkat stres yang lebih tinggi dan prestasi belajar yang lebih rendah." Oleh karena itu, penting untuk menemukan solusi yang dapat mendorong peserta didik untuk kembali mengutamakan kerja sama dan gotong royong dalam belajar.
Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah melalui pembelajaran berbasis praktik, seperti pembuatan canang sari. Canang sari, yang merupakan bagian dari tradisi Bali dalam upacara keagamaan, dapat menjadi media pembelajaran yang efektif untuk mengajarkan nilai gotong royong. Sebagaimana dikemukakan oleh Sudarsana (2017), "melalui praktik pembuatan canang sari, siswa dapat belajar pentingnya kerjasama, tanggung jawab, dan saling menghargai peran masing-masing dalam mencapai hasil yang diinginkan."
Praktikum pembuatan canang sari tidak hanya memperkenalkan siswa pada aspek budaya dan keagamaan, tetapi juga menumbuhkan keterampilan kolaboratif yang esensial dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembuatan canang sari yang melibatkan berbagai langkah dan bahan membutuhkan kerja sama yang baik antar siswa. Sebagaimana dijelaskan oleh Ratna (2018), "setiap tahap dalam pembuatan canang sari memerlukan kontribusi dari setiap anggota kelompok, sehingga tidak ada yang bisa bekerja sendiri tanpa bantuan orang lain."
Budiana, I. G. (2015). "Pawongan dalam Tri Hita Karana berfungsi sebagai prinsip dasar dalam menjaga harmoni sosial dan memperkuat rasa kebersamaan di antara anggota komunitas." Jurnal Kebudayaan Bali, 8(1), 22-35.
Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. SAGE Publications.
Dewantara, K. H. (2013). Pendidikan dalam Kebudayaan. Pustaka Pelajar.
Drost, A. (2015). "Kontekstualisasi pendidikan karakter melalui budaya lokal membantu siswa untuk lebih dekat dengan nilai-nilai yang diajarkan, karena mereka dapat melihat aplikasi nyata dari nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari." Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 21(2), 112-125.
Geertz, C. (1961). The Religion of Java. University of Chicago Press.
Hidayat, N. (2018). "Implementasi nilai budaya lokal dalam pendidikan karakter tidak hanya memperkuat identitas budaya siswa tetapi juga meningkatkan keterampilan sosial mereka melalui praktik langsung." Jurnal Pendidikan Karakter, 10(2), 45-58.
Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (2014). Cooperation and Competition: Theory and Research.
Interaction Book Company.
Koesoema, D. A. (2007). Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global.
Gramedia.
Ki Hadjar Dewantara. (2013). Pendidikan dalam Kebudayaan. Pustaka Pelajar.
Lickona, T. (1991). Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility. Bantam Books.
Munandar, A. (2016). "Media pembelajaran berbasis budaya lokal tidak hanya memperkaya proses belajar mengajar, tetapi juga menjadi alat yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai karakter yang relevan dengan konteks kehidupan siswa." Jurnal Teknologi Pendidikan, 18(3), 78-90.
Pranoto, A. (2021). "Mengubah Pola Pikir Siswa Melalui Kolaborasi dalam Pembelajaran." Jurnal Pendidikan Karakter, 12(1), 45-56.
Rachmadi, A. (2019). "Dampak Individualisme pada Prestasi Belajar Siswa." Jurnal Psikologi Pendidikan, 15(2), 98-110.
Ratna, D. (2018). Budaya dan Tradisi Bali dalam Pendidikan. Pustaka Pelajar.
Sudarsana, I. K. (2017). Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Lokal: Canang Sasi dalam Upacara Keagamaan di Bali. Udayana University Press.
Suryadi, R. (2020). "Pengaruh Individualisme terhadap Dinamika Kelas dan Prestasi Belajar." Jurnal Ilmu Pendidikan, 18(3), 112-123.
Tilaar, H. A. R. (2009). Mengindonesiakan Kembali Pendidikan Kita. Rineka Cipta.
Wibowo, S. (2020). "Pendidikan Karakter dalam Kurikulum Sekolah: Sebuah Pendekatan Holistik." Jurnal Pendidikan Nasional, 10(4), 123-134.